Usai pemutaran Film Dokumenter Pulang Rimba karya Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) yang berlangsung di Omah Betakan, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (3/1/2023), memantik diskusi panjang.
Permasalahan yang dialami Suku Anak Dalam di hutan tropis Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo hingga Kabupaten Batanghari atau sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Provinsi Jambi, sebagaimana tergambar dalam film tersebut cukup kompleks.
Bagaimana kelompok minoritas suku adat yang semula bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu di hutan kemudian harus berhadapan dan beradaptasi dengan moderenitas. Pendidikan masih menjadi hal yang mahal. Tokoh Pauzan, adalah segelintir remaja Suku Anak Dalam yang ditampilkan dalam film ini sedang berjuang keras menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.
[caption id="attachment_14876" align="alignnone" width="768"] Sutradara Film Dokumenter Pulang Rimba, Rahmat Triguna alias Mamato (kiri), saat memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan film usai pemutaran perdana di Omah Betakan Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (3/1/2023). (foto abdul mughis)[/caption]
Sutradara Film Dokumenter Pulang Rimba, Rahmat Triguna alias Mamato (kiri), saat memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan film usai pemutaran perdana di Omah Betakan Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (3/1/2023). (foto abdul mughis)[/caption]
Berlapis-lapis faktor permasalahan Suku Anak Dalam terungkap. Pro kontra ide dan gagasan tak pelak muncul dalam diskusi ini. Namun hal itu semata-mata sebagai upaya mengurai ‘benang kusut’ permasalahan yang dialami kelompok minoritas seperti Suku Anak Dalam maupun komunitas adat yang lain.
BACA JUGA: Film Pulang Rimba: Perjuangan Menyelamatkan Suku Anak Dalam yang Terancam Punah
Knowledge Manager & Communication Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemawan Pontianak, Muhammad Reza menilai permasalah kompleks yang menimpa Suku Anak Dalam bermula dari masalah alihfungsi lahan hutan menjadi kebun sawit yang tidak memperhatikan hak hidup komunitas suku adat.
“Berbicara permasalahan sawit, sama saja melawan raksasa,” ujarnya menghangatkan forum diskusi.
Pasalnya, pengelolaan perkebunan sawit dipastikan melibatkan perusahaan yang bermain dalam skala besar. Tentu saja memiliki kekuatan besar pula. Tetapi muncul pula pertanyaan apakah mungkin, “raksasa” tersebut bisa berperan menjadi “raksasa yang santun”? Misalnya, perusahaan tersebut agar dapat terlibat dalam upaya membangun pendidikan untuk suku adat yang terkena dampak.
“Peluang perubahan tetap ada. Waktu kami melakukan riset juga melibatkan perusahaan sebagai stakeholder. Memang, ada etikad baik dari mereka. Tapi yang jadi masalah sebetulnya ekspansinya itu lho, ‘memakan’ banyak orang, ya kan?” katanya.
Keinginan Mereka untuk Berubah Cukup Tinggi
Wakil Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jambi Fuad Muchlis mengatakan secara garis besar, Suku Anak Dalam terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok Suku Anak Dalam yang masih memegang tradisi nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal di dalam hutan.
“Kedua, kelompok bediom, yakni mereka sudah menyatu atau bergabung dengan masyarakat desa. Sudah berinteraksi akibat pernikahan, pekerjaan dan lain-lain. Umumnya sudah berbaur dengan masyarakat pada umumnya,” katanya.
Ketiga, kelompok transisi, yakni kelompok Suku Anak Dalam yang belum mampu beradaptasi dengan dunia luar, tapi bergantung terhadap hutan sudah tidak mungkin lagi karena sumberdaya di hutan sudah semakin menipis.
“Sementara populasi jumlah mereka semakin berkurang. Inilah yang pada umumnya menjadi sumber konflik. Terutama dengan perusahaan, seperti mengambil sawit milik perusahaan, mengambil sawit milik petani dan seterusnya,” beber dia.
[caption id="attachment_14877" align="alignnone" width="768"] Suasana diskusi usai pemutaran Film Dokumenter Pulang Rimba karya Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) yang berlangsung di Omah Betakan, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (3/1/2023). (foto abdul mughis)[/caption]
Suasana diskusi usai pemutaran Film Dokumenter Pulang Rimba karya Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) yang berlangsung di Omah Betakan, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (3/1/2023). (foto abdul mughis)[/caption]
Menurutnya kondisi kelompok transisi ini juga penting untuk disorot, karena jumlah kelompok transisi ini semakin lama semakin bertambah. “Tentu, jawabannya adalah pendidikan. Apakah pendidikan formal atau pendidikan non formal, pelatihan teknik budidaya misalnya, sehingga ketergantungan mereka terhadap sumberdaya hutan bisa teratasi,” katanya.
Hasil studi yang dilakukan oleh pihaknya terhadap permasalahan Suku Anak Dalam menunjukkan bahwa minat atau keinginan mereka untuk berubah cukup tinggi. “Kalau selama ini ada anggapan bahwa mereka memegang prinsip tidak mau menyekolahkan anak, maka lambat laun semakin berubah. Mereka sebetulnya sudah memiliki keinginan kuat terhadap anak-anaknya untuk sekolah,” katanya.
Tradisi Pernikahan Dini
CEO LSM Pundi Sumatra, Dewi Yunita Widiarti mengatakan, persoalan yang tidak kalah penting adalah mengenai pemahaman kepada mereka perihal mengapa pendidikan itu penting. “Kedua, mengenai fasilitas. Kebanyakan mereka masih khawatir bagaimana biaya untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Mulai dari seragam, alat tulis, tas, uang jajan anak, hingga akses transportasi yang cukup jauh,” katanya.
BACA JUGA: Perempuan yang Melawan Adat Pernikahan Anak Demi Kuliah
Persoalan lain yang menjadi kendala mengenai budaya misalnya pernikahan dini. Mereka memiliki tradisi menikah di usia dini. Usia belasan tahun sudah menikah. Akibatnya, banyak ditemui kasus putus sekolah.
“Bahkan laki-laki seusia Pauzan, 24 tahun, di sana biasanya sudah punya dua-tiga anak. Apalagi perempuan. Ini menjadi persoalan serius yang harus disoroti. Persoalan yang terjadi di Suku Anak Dalam ini harus menjadi perhatian banyak pihak,” ungkap dia.
[caption id="attachment_14878" align="alignnone" width="768"] Suasana diskusi usai pemutaran Film Dokumenter Pulang Rimba karya Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) yang berlangsung di Omah Betakan, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (3/1/2023). (foto abdul mughis)[/caption]
Suasana diskusi usai pemutaran Film Dokumenter Pulang Rimba karya Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) yang berlangsung di Omah Betakan, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (3/1/2023). (foto abdul mughis)[/caption]
Rektor Universitas Jambi (UNJ), Prof Sutrisna menjelaskan sedikitnya ada empat hal yang perlu dicermati, yakni; human, structural change, keseimbangan, dan mata rantai yang belum terkoneksi.
“Saya sepakat, cerita Pauzan ini sebagai pemantik saja. Human, adalah untuk menjadi ‘manusia yang manusia’ kuncinya ya pendidikan. Tidak harus pendidikan formal,” katanya.
Dia menilai, cerita dalam Film Pulang Rimba yang mengisahkan perjuangan seorang pemuda Suku Anak Dalam bernama Pauzan dalam menempuh perguruan tinggi ini masih perlu diperdalam.
“Yang menjadi persoalan di film ini, bahwa permasalahan yang diangkat adalah pendidikan tinggi. Ada mata rantai yang terputus. Mestinya harus dilihat dari SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana, ada proses panjang sebelumnya,” ujarnya.
Kesinambungan yang Seimbang
Menurutnya, ‘menjadi manusia’ melalui pendidikan ini secara ‘structural change’ perlu dicermati. Siapa yang konsentrasi tanggung jawab kepada pendidikan SD, SMP dan SMA ini perlu dielaborasi.
“Perlu ada kesinambungan yang seimbang. Karena kalau tidak seimbang, akan ada persoalan di berbagai dimensi. Misalnya berbenturan dengan perusahaan, warga lain dan seterusnya. Apapun kalau kita berbicara alam, maka butuh keseimbangan,” bebernya.
Sutrisna menilai, persoalan Suku Anak Dalam ini menjadi laboratorium yang luar biasa. Tapi cerita dalam film ini terkesan langsung melompat ke pendidikan tinggi. “Memang, ini pekerjaan besar dan tidak mudah. Pauzan bisa sampai di sini adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Butuh ketelatenan, kesabaran, pelibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, pusat, dan seterusnya. Mengkoneksikan itu tidak gampang.
Maka, lanjut dia, diperlukan riset lebih mendalam untuk mengetahui “apa yang Anda mau?” bukan “yang kami mau”. “Pada ujungnya harus mengubah “habit” (kebiasaan) untuk kehidupan yang lebih baik. Etos kerja membutuhkan penempaan. Itu harus didampingi. Pertanyaannya, siapa yang akan siap mendampingi?,” ujarnya dalam forum diskusi tersebut.
Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), Noor Huda Ismail mengatakan sedikitnya ada empat prinsip dalam kerja yang dijalankan oleh KPP, yakni merasakan (feel), membayangkan (imagine), melakukan (do) dan berbagi (share). "Kami sangat menghargai imajinasi dan kreativitas," ungkapnya. (*)
Diskusi Film Pulang Rimba: Mengurai ‘Benang Kusut’ Permasalahan Suku Anak Dalam
Newsby Abdul Mughis 4 Januari 2023 9:22 WIB




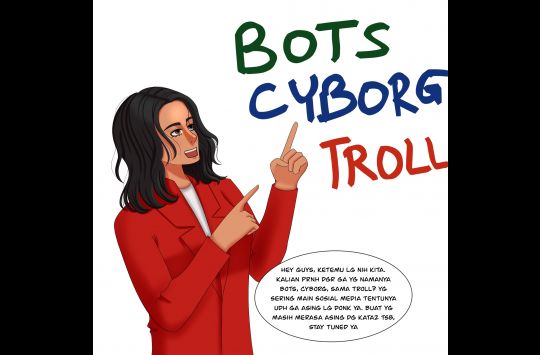
Komentar