Direktur Pendampingan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Khairiroh Maknunah prihatin dengan banyaknya anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme di Indonesia. Menurut sosok yang akrab disapa Nuna itu berdasarkan data dari YPP, hingga tahun 2019 ada 19 orang anak-anak yang terlibat kasus terorisme. Namun menurut Nuna dari jumlah anak-anak yang ditangkap tersebut tidak semuanya diproses hukum di pesidangan.
“Kami ingin spesipik ingin mendalami anak. Ternyata cukup banyak anak-anak yang terlibat dalam terorisme. Akhirnya kita dalami semakin banyak. Ketika itu kami belum punya datanya secara berapa anak-anak yang terlibat terorisme. Akhirnya kita kumpulkan data secara mandiri. Totalnya ada yang ditangkap 19 anak tahuun 2019. Tidak semuanya diproses hukum di persidangan,” kata Nuna dalam acara diskusi online yang diadakan oleh Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) dan Ruangobrol.id Pada Hari Kamis, 30 Juli 2020 lalu.
Lebih lanjut berdasarkan catatan Nuna, sudah ada tujuh anak yang bebas. Dari jumlah tersebut satu orang kembali melakukan aksi teror. Yaitu Darwin Gobel yang melakukan penyerangan terhadap petugas polisi di Bank Mandiri Syariah di Poso pada April 2020 lalu. Darwin sendiri tewas karena melawan aparat keamanan.
“Anak-anak itu ditempatkan di Laspas Khusus anak (LPKA). Sudah ada 7 yang sudah bebas. 1 orang kembali melakukan aksi teror. Dia ditangkap masih anak, keluarnya sudah bukan anak-anak lagi. Yang masih di LPKA, 4 anak. Dipindahkan ke LP 4 anak,” kata Nuna dalam diskusi dengan tema ‘Anak-anak dalam Terorisme dan Solusinya’ itu.
Secara usia, anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme di rentang umur 15 tahun hingga 17 tahun. Menariknya menurut Nuna ada anak-anak yang ditangkap bersamaan dengan saudaranya. Ada juga anak-anak yang ditangkap bersama orang tuanya.
“Usia anak-anak yang ditangkap dalam kasus terorisme adalah 15 hingga 17 tahun. Ada juga kakak adik. Ditangkap ada juga yang bersama orang tuanya,” kata Nuna lagi dalam diskusi yang dipandu oleh Direktur Eksekutif PAKAR Adhe Bakti tersebut.
Secara pendidikan lulusan anak-anak yang teribat dalam kasus terorisme beragam. Yaitu lulusan SMP hingga ada yang masih mengabdi di pesantren. Nuna mengakui jika tempat pendidikan sangat berpengaruh menjadikan anak-anak menjadi pelaku teror. Karena menurutnya Lembaga pendidikan tersebut berafiliasi dengan kelompok teroris.
“Mereka ada yang lulusan MTS, Belum lulus SMP, Belum lulus SMA. Ada juga masih mengabdi di pesantren.Saya menemukan sekitar 36p Persen berpengaruh karena lembaga itu berafiliasi,” imbuhnya
Selain faktor pendidikan, menurut Nuna yang sangat berpengaruh bagi anak teroris adalah dari pemahaman orang tua mereka sendiri. Berdasarkan survey yang YPP lakukan terhadap orang tua mereka, ada 55 persen orangtua yang setuju dengan apa yang anak-anak mereka lakukan. Sedangkan 39 persen orangtua tidak setuju dengan tindakan anak-anak mereka. Sisanya mereka tidak mau menjawab.
“Bahwa ada 55 persen Ortu yang sepakat yang dilakukan anak-anak.Ada 39 persen yang tidak setuju, sisanya tidak menjawab. Ada yang bersama-sama dengan orangtua kita dampingi anak-anaknya. Rata-rata mereka ini teradikalisasi melalui ortunya,” tuturnya.
Soal hak perlindungan anak menurut Nuna masih terjadi beberapa kasus kekerasan saat anak-anak ditangkap maupun saat penydidikan. Sementara ketika di pengadilan, anak-anak cenderung mendapatkan vonis yang sangat tinggi. Meski perannya hanya menyembunyikan informasi.
Terkait rehabilitasi, Nuna menyampaikan jika LAPAS belum siap. Meski sudah ada LPKA, karena belum ada rutan khusus anak. Selain itu belum semua LAPAS anak belum siap melakukan rehabilitasi.
“Jangankan ideologi yang perubahan prilaku saja mereka belum. Karena ini nanti akan berdampak Saat anak di lapas ada proses titik balik Yang bisa jadi momentum untuk mengedgentmen,” kata Ibu satu anak itu.
Sementara itu Program Manager Society Against Radicalism and Violent Extremism (SeRVE), Mayolisia Ekayanti membenarkan pengaruh orang tua sangat besar bagi anak-anak dalam terlibat kasus teroris. Bahkan menurut Eka cara yang paling ektrims adalah dengan memisahkan anak dari orang tua yang terlibat dalam kelompok teror. Namun Eka mengakui hal itu tidak manusiawi.
“Kalau mau ikut ego ya maunya dipisahain, tapi gak mungkin memisahkan anak dengan orangtuanya. Saya kira perlu kerjasama dengan bersama. Kita perlu edukasi masyarakat. Jangan mudah menstigma,”
Selain itu lanjut Eka, pasca orang tuanya ditangkap, keluarga yang ditinggalkan jatuh pada kemiskinan. Masalahnya yang datang membantu bukanlah pemerintah. Melainkan teman-teman satu kelompok dengan ayahnya. Sehingga hal itu turut mempengaruhi berhasil tidaknya anak-anak mengikuti program yang dijalankan oleh CSO.
“Yang datang biasanya teman-teman Abinya. Sehingga ada upaya membantu mereka dengan memberikan beasiswa ke sekolah yang masih sealiran. Bahkan di sekolah ini sudah dipertontonkan video kekerasan yang ada di negara Muslim. Anak-anak ini harus disentuh secara terus menerus. Karena kalau gak selesai sekarang. Akan menjadi ancaman di masa depan,” imbuhnya
Sedangkan Peneliti Division for Applied Social Psychology Research/DASPR) Erni Kurniati lebih banyak membagikan pengalamannya mendampingi anak-anak yang orang tuanya terjerat kasus terorisme. Intervensi yang dilakukan terhadap anak-anak napiter adalah menjelaskan secara luas bahwa masyarakat Indonesia sangat toleran. Selain itu perlunya kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun CSO.
“Bikin taman baca merupakan salah satu solusi. Di komunitas ini kami berharap mengkonter ideologi keras yang intoleran dan memberikan dukungan sosial terutama bagi napiter yang baru pulang. Otomatis adanya lembaga ini. Kita bisa kasih edukasi dan support,” pungkasnya
Anak-anak Pelaku Teror Terpengaruh dari Orangtuanya
Newsby Akhmad Kusairi 10 Agustus 2020 11:52 WIB


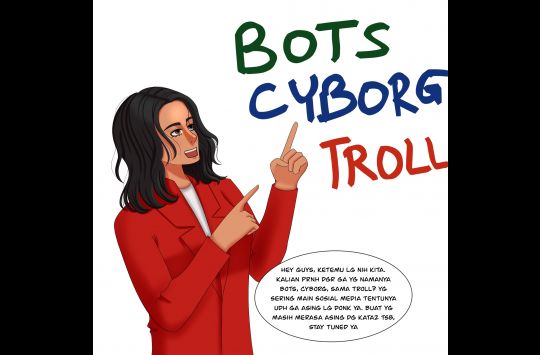

Komentar